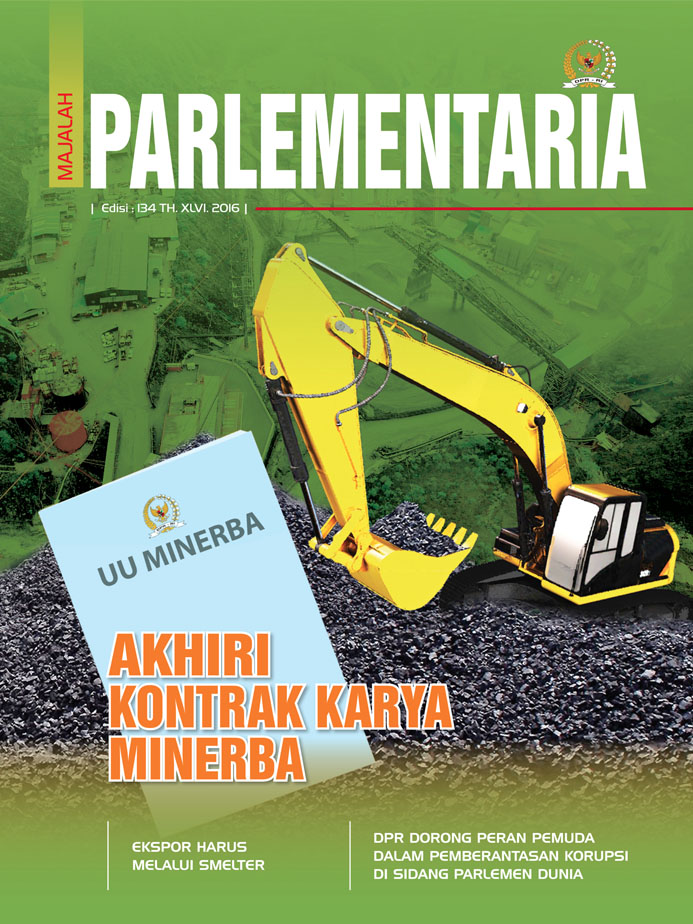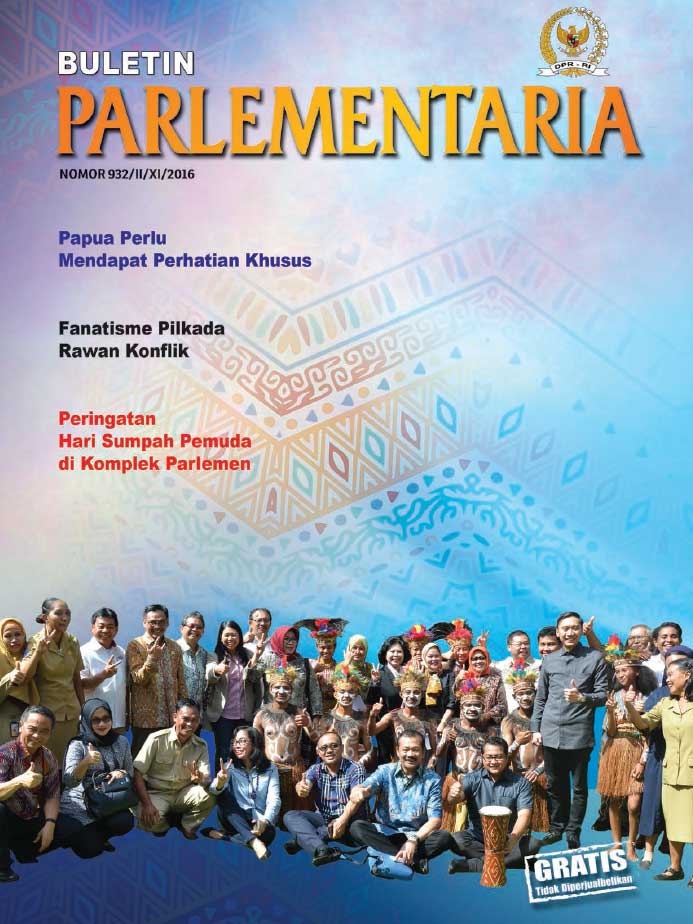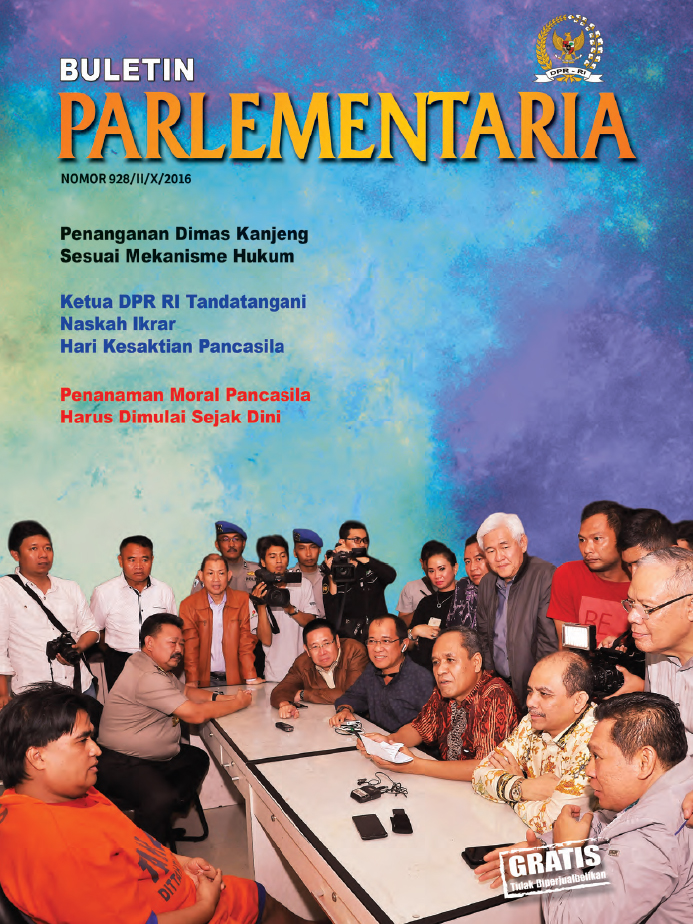- Minggu, 10 Agustus 2025
- Majalah Tempo
- Tempo English
- Koran Tempo
- Komunika
- Tempo Store
- Fokus
- Edisi Khusus
- Indonesiana
- Business Update
- Indikator
- Tempo Channel
- Live Score
Tweets by @DPR_RI
INFO DPR+
1
IPU Mengadopsi Resolusi Status Kota Jerusalem
2Anggota BURT: Penataan Parlemen untuk Kepentingan Bersama Bukan Pribadi
3Parlemen Indonesia Desak Parlemen Asia Bersatu
4Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
5Legislator Apresiasi Masukan Renstra DPR dari Berbagai Kalangan
6Renstra Menata DPR Menuju Parlemen Modern
7DPR Minta Australia Relaksasi Hambatan Non-Tarif
8Masa Sidang Pertama DPR Selesaikan Delapan RUU
9BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
10Wakil Ketua DPR Terima Dubes Finlandia
-

DPR RI - DPR RI DESAK PEMERINTAH SEGERA BENTUK BADAN PANGAN NASIONAL
-

DPR RI - DPR RI HARUS ADA KONSEKUENSI HUKUM DARI HASIL SURVEY
-

DPR RI - BK DPR RI GELAR FGD DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SOLO
-

DPR RI - TIMWAS PMI DESAK PEMERINTAH BANGUN EARLY WARNING SISTEM BAGI PMI
-

DPR RI - WAKIL RAKYAT - SYAIFULLAH TAMLIHA
-

DPR RI - KOMISI IV DPR RI DUKUNG PERKEBUNAN CENGKEH DI MALUKU UTARA
VIDEO+
Komisi IX Soroti Pengawasan DAK Kesehatan ke Daerah
Kamis, 13 April 2017

Komisi IX Soroti Pengawasan DAK Kesehatan ke Daerah
Anggaran kesehatan ke daerah berubah ketika telah menjadi bagian dari dana alokasi khusus (DAK). Hal ini menyebabkan Komisi IX, yang membidangi masalah kesehatan, mengalami kesulitan melakukan pengawasan.
“Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih. Kadang-kadang daerah, ketika kami kunjungi, meminta DAK kesehatan dan kami perjuangkan. Tapi mereka kemudian komplain karena akhirnya tidak mendapatkannya, sedangkan daerah lain, yang tidak minta, malah dapat,” kata anggota Panja DAK Kesehatan Komisi IX DPR RI, Dewi Asmara, saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Bappenas dan Dirjen Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi IX, Kamis, 13 April 2017.
Kata Dewi, saat Komisi IX menanyakan kepada menteri terkait (Kementerian Kesehatan) apakah DAK kesehatan bergantung kepada mereka, dikatakan itu ditentukan Kementerian Keuangan. “Inilah yang terjadi, bolak-balik, sehingga tidak ada kejelasan. Kami sebagai yang mengatur fungsi pengawasan dan bertanggung jawab terhadap anggaran kesehatan, tentunya harus melihat kalau memang ada DAK kesehatan, katakanlah untuk perbaikan puskesmas, ketika kami kunjungan kerja, itu kok tidak terlihat?” tuturnya.
Dewi melihat adanya egosektoral antara pusat dan daerah. “Bupati jalannya maunya bagaimana, Kementerian Kesehatan bagaimana. Tapi kita tidak bisa ikut campur. Jadi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab menyusun DAK kesehatan itu?” katanya.
Padahal, kata Dewi, ihwal DAK kesehatan ini, Komisi IX benar-benar perlu kejelasan mengenai pelaksanaannya di daerah. “Tapi saat ini menjadi tidak bisa dikontrol. Kami yang menyetujui anggarannya, tapi kami tidak bisa melakukan pengawasan. Jangankan kami, institusi Kementerian Kesehatan saja kadang tidak bisa,” ucapnya.
Dengan adanya otonomi daerah, dinas kesehatan di daerah tidak bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan lagi, tapi bupati sebagai pejabat daerah. “Ini tentu menyulitkan dalam fungsi pengawasan. Padahal, sebagai komisi yang membawahi kesehatan, sudah sepantasnya kami mengawasi dana kesehatan yang disalurkan ke daerah,” ujarnya.
Karena itu, Dewi tidak setuju jika DAK kesehatan menjadi satu dengan DAK yang masuk sebagai afirmatif. “Karena tidak ada kontrol dari pusat. Berbeda kalau DAK fisik, seperti untuk jalan, jembatan. Itu masih diawasi Kementerian PUPR. Artinya, mereka masih punya garis komando. Tapi kalau kesehatan tidak. Itu kenyataan sebenarnya,” tuturnya.
Jadi, meski secara jumlah masih tetap sama, Dewi menegaskan, anggaran kesehatan untuk daerah tidak boleh dicampur dengan DAK fisik. “Karena itu akan membuat Komisi IX tidak tahu waktu dianggarkan. Ketika mau mengawasi juga tidak tahu itu jadinya seperti apa, di mana. Memang ada audit dari BPKP, tapi karena itu menyangkut kesehatan, kami juga mempunyai kewenangan di situ. Kami mempunyai fungsi kontrol terhadap dana-dana kesehatan yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Meski ada Undang-Undang Otonomi Daerah, mungkin itu tidak dilepas begitu saja,” kata Dewi.
Anggota Panja DAK Kesehatan lainnya, Okky Asokawati, mengutarakan, DAK kesehatan sulit dikontrol karena memang pimpinan daerah belum tentu memiliki keberpihakan yang sama dengan kementerian teknis terkait (Kementerian Kesehatan). “Karena informasi yang saya dapatkan, anggaran yang turun ke sebuah daerah itu bentuknya gelondongan dan bukan per program. Ini bisa terjadi missplacement atau displacement, karena pemimpin daerahnya mungkin mempunyai kepentingan tersendiri,” kata Okky. (*)
-

Monday, 12 March 2018
Peresmian Gedung Grha Suara Muhammadiyah
-

Wednesday, 23 November 2016
Wakil Ketua DPR RI Aher Gelar Coffee Morning Panas Bumi
-

Friday, 18 November 2016
Ketua DPR RI Ade Komarudin terima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
-

Tuesday, 08 November 2016
Diskusi Dialektika
-

Thursday, 20 October 2016
Kopi Darat DPR Bersama Kementerian dan Lembaga
-

Monday, 17 October 2016
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
FOTO TERKINI
PARLEMENTARIA+
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA