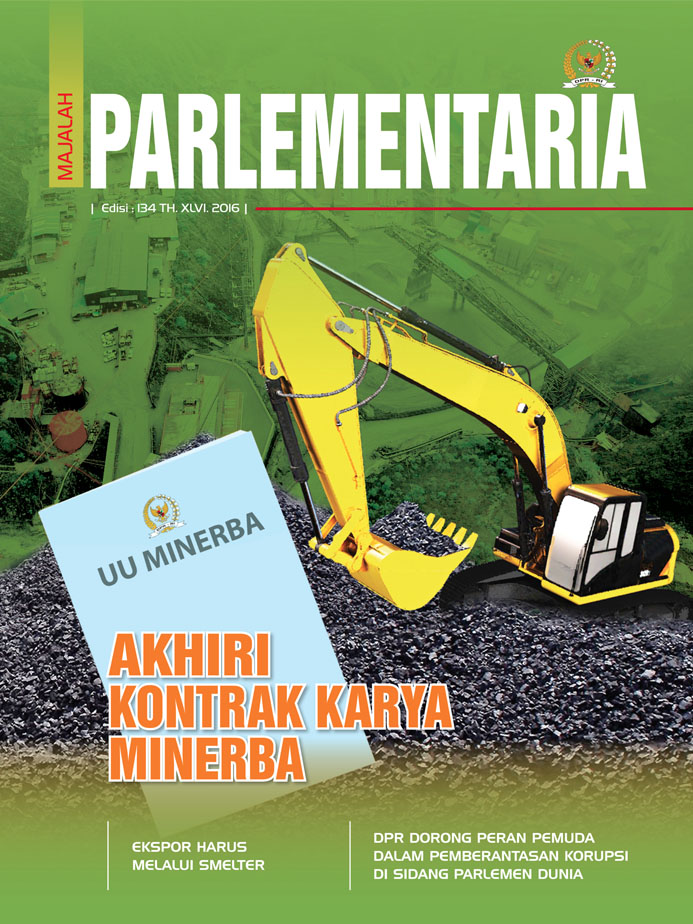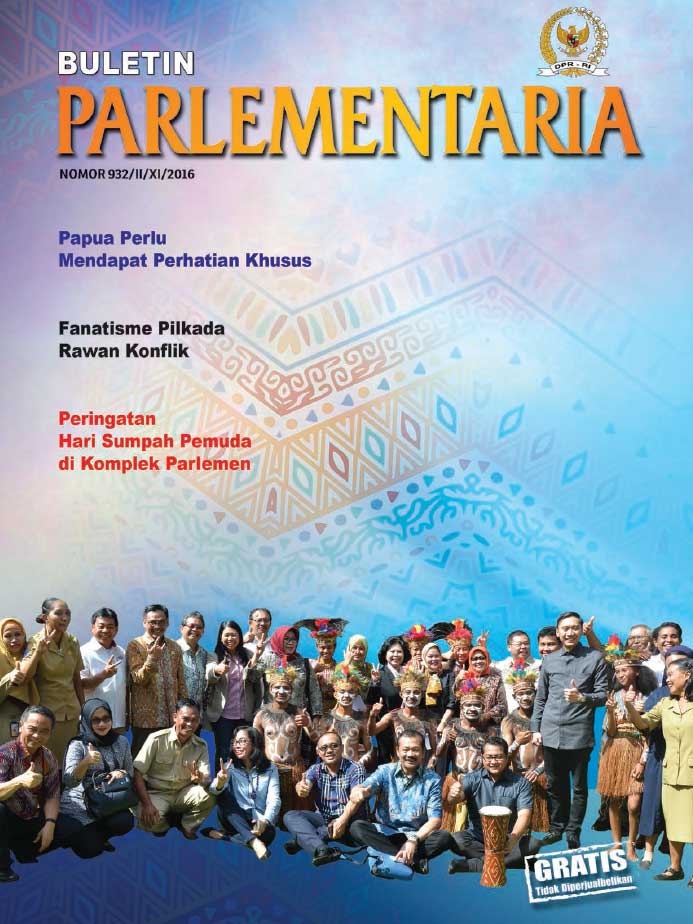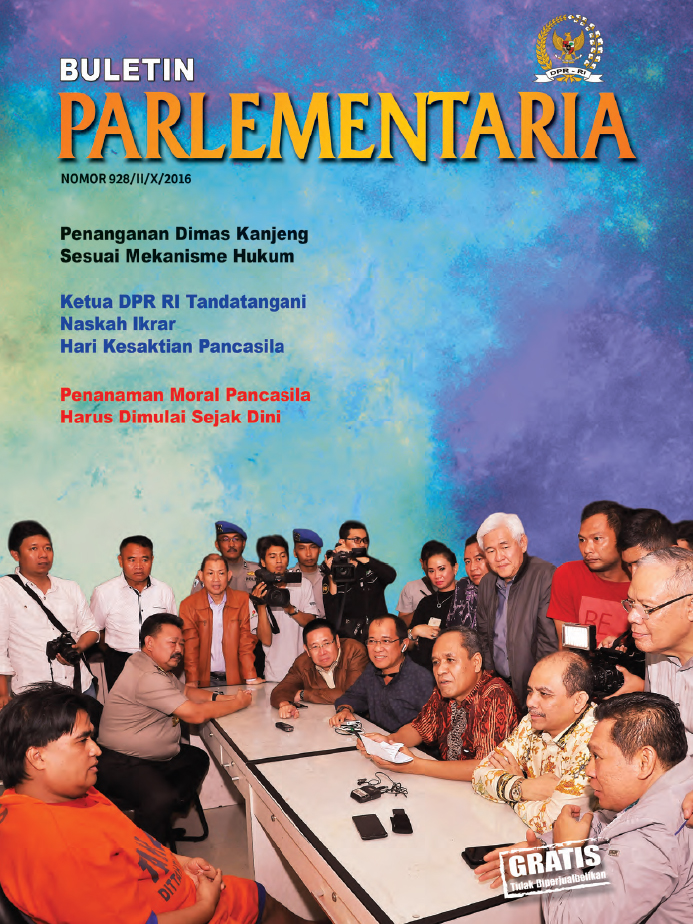- Senin, 09 Juni 2025
- Majalah Tempo
- Tempo English
- Koran Tempo
- Komunika
- Tempo Store
- Fokus
- Edisi Khusus
- Indonesiana
- Business Update
- Indikator
- Tempo Channel
- Live Score
Tweets by @DPR_RI
INFO DPR+
1
IPU Mengadopsi Resolusi Status Kota Jerusalem
2Anggota BURT: Penataan Parlemen untuk Kepentingan Bersama Bukan Pribadi
3Parlemen Indonesia Desak Parlemen Asia Bersatu
4Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
5Legislator Apresiasi Masukan Renstra DPR dari Berbagai Kalangan
6Renstra Menata DPR Menuju Parlemen Modern
7DPR Minta Australia Relaksasi Hambatan Non-Tarif
8Masa Sidang Pertama DPR Selesaikan Delapan RUU
9BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
10Wakil Ketua DPR Terima Dubes Finlandia
-

DPR RI - DPR RI DESAK PEMERINTAH SEGERA BENTUK BADAN PANGAN NASIONAL
-

DPR RI - DPR RI HARUS ADA KONSEKUENSI HUKUM DARI HASIL SURVEY
-

DPR RI - BK DPR RI GELAR FGD DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SOLO
-

DPR RI - TIMWAS PMI DESAK PEMERINTAH BANGUN EARLY WARNING SISTEM BAGI PMI
-

DPR RI - WAKIL RAKYAT - SYAIFULLAH TAMLIHA
-

DPR RI - KOMISI IV DPR RI DUKUNG PERKEBUNAN CENGKEH DI MALUKU UTARA
VIDEO+
Pasal Penodaan Agama Bisa Diujimaterikan
Selasa, 16 Mei 2017

Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama, pada tahun 2009, 2010 dan 2012 sudah pernah digugat masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat yang tidak puas dengan Pasal 156a KUHP, yang dianggap pasal karet dan diskriminatif terkait dengan penodaan agama, disarankan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pada 2010 dan 2012, pasal itu masih ditetapkan sebagai pasal penodaan agama. Namun putusan MK itu bisa berubah jika masyarakat keberatan.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, dalam forum legislasi “Penghapusan Pasal 156a UU KUHP, Pasal Karet?” bersama pakar hukum tata negara, Refly Harun, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.
“Pada 2009, 2010 dan 2012, Pasal 156a KUHP sudah pernah digugat masyarakat sipil ke MK, dan pada 19 April 2010, MK mengeluarkan Keputusan Nomor 140 dengan menyatakan pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, saya meminta norma pasal itu diperbaiki dan disempurnakan agar tidak menjadi pasal karet,” kata Sekjen DPP PPP itu.
Dengan begitu, kata Arsul, Pasal 156a sudah tidak ada masalah. Namun, kalau masyarakat menggugat ke MK, kemungkinan putusannya akan berbeda dengan putusan sebelumnya bisa terjadi. Ia mencontohkan hukuman mati di Amerika Serikat pada 1971 diputus inkonstitusional, tapi pada 1976 diputus konstitusional karena masyarakat menggugat. “Makanya, 28 negara bagian Amerika saat ini masih menerapkan hukuman mati dan 11 negara mengeksekusi mati,” tuturnya.
DPR dan pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang KUHP. Khusus Pasal 156a, ada dua kategori mengenai hal yang dimaksud dengan penghinaan agama. “Itu tergantung pada penafsiran hakim. Selain itu, pasal ini belum menjadi kesepakatan fraksi di DPR. Pada Pasal 348 hingga 353 Undang-Undang KUHP, fraksi meminta merumuskan perbuatan apa yang termasuk penghinaan agama agar hakim tidak subyektif dan diskriminatif,” ujarnya.
Hanya, Arsul menolak kalau pasal itu dihapus. Sebab, menurutnya, hukum itu berfungsi sebagai kendali sosial dan di negara-negara maju pun masih berlaku. “Masalah agama ini sensitif. Kalau tanpa hukum, masyarakat bisa main hakim sendiri sehingga akibatnya akan makin buruk,” ucapnya.
Adapun Refly Harun menegaskan bahwa Pasal 156a bukan kitab suci. Sehingga, kalau dinilai diskriminatif, seharusnya diperbaiki. Sebab, undang-undang yang baik untuk diterapkan adalah undang-undang yang perumusannya tidak multitafsir dan tidak diskriminatif. Kalau multitafsir, berarti undang-undang itu masih buruk dan bisa menimbulkan otoritarianisme mayoritas atas minoritas dan sebaliknya.
Pasal 156a lahir karena Presiden Sukarno waktu itu ingin mengakomodasi permintaan mayoritas kelompok beragama. Sedangkan dari sisi negara, kata Refly, negara harus melindungi semua warga negara. “Tak ada mayoritas ataupun minoritas. Jadi silakan masyarakat menggugat ke MK atas pasal 156a kalau dinilai diskriminatif,” katanya.
Menurut Refly, harus ada rumusan yang jelas dalam Pasal 156a karena ada dua kategori. Pertama, hatespeech (ujaran kebencian) yang sifatnya guyonan, bercanda, dan olok-olokan. Kedua, yang nyata-nyata melakukan perbuatan yang dilarang, seperti menginjak-injak kitab suci. “Jangan sampai ini terjadi di pilpres 2019 meski politik kita masih menghalalkan segala cara,” tuturnya. (*)
-

Monday, 12 March 2018
Peresmian Gedung Grha Suara Muhammadiyah
-

Wednesday, 23 November 2016
Wakil Ketua DPR RI Aher Gelar Coffee Morning Panas Bumi
-

Friday, 18 November 2016
Ketua DPR RI Ade Komarudin terima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
-

Tuesday, 08 November 2016
Diskusi Dialektika
-

Thursday, 20 October 2016
Kopi Darat DPR Bersama Kementerian dan Lembaga
-

Monday, 17 October 2016
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
FOTO TERKINI
PARLEMENTARIA+
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA