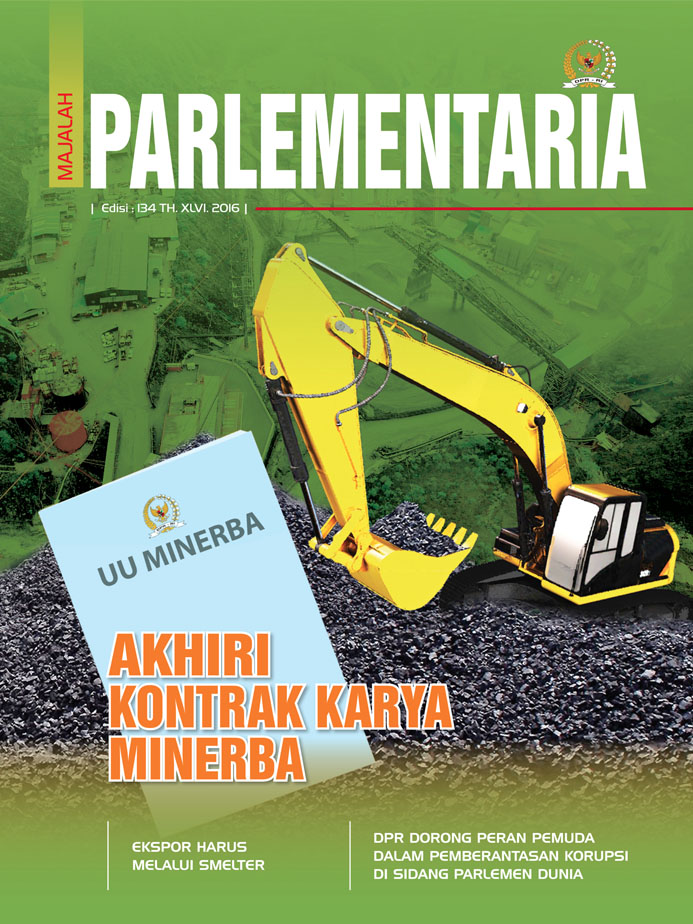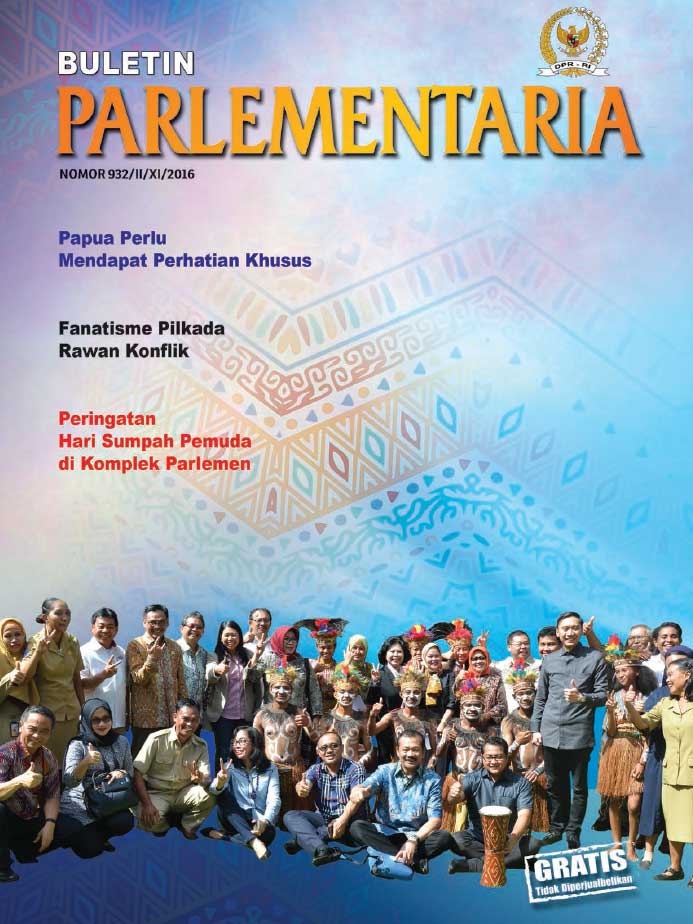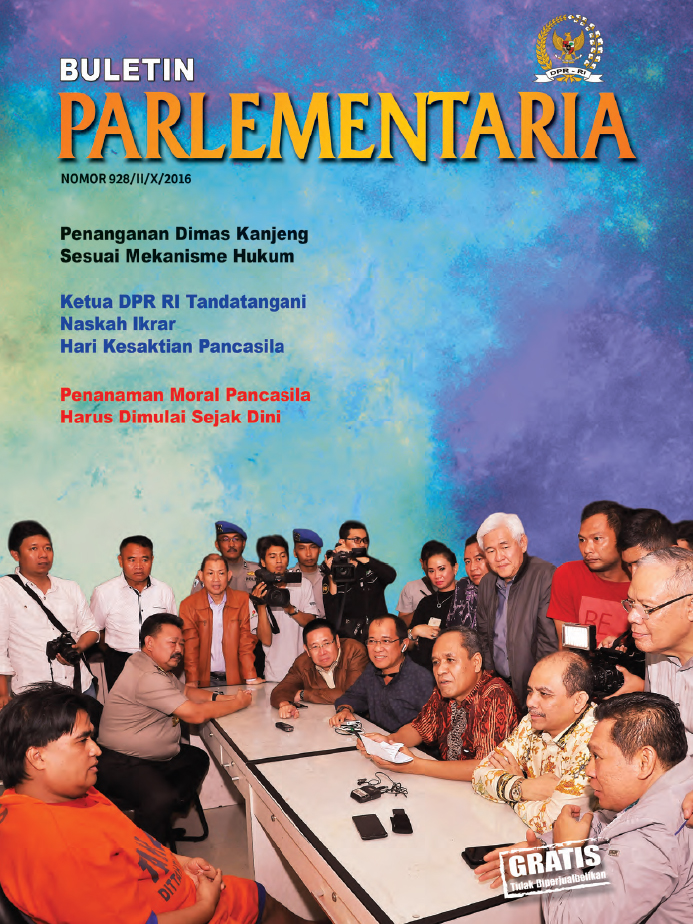- Jumat, 06 Juni 2025
- Majalah Tempo
- Tempo English
- Koran Tempo
- Komunika
- Tempo Store
- Fokus
- Edisi Khusus
- Indonesiana
- Business Update
- Indikator
- Tempo Channel
- Live Score
Tweets by @DPR_RI
INFO DPR+
1
IPU Mengadopsi Resolusi Status Kota Jerusalem
2Anggota BURT: Penataan Parlemen untuk Kepentingan Bersama Bukan Pribadi
3Parlemen Indonesia Desak Parlemen Asia Bersatu
4Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
5Legislator Apresiasi Masukan Renstra DPR dari Berbagai Kalangan
6Renstra Menata DPR Menuju Parlemen Modern
7DPR Minta Australia Relaksasi Hambatan Non-Tarif
8Masa Sidang Pertama DPR Selesaikan Delapan RUU
9BURT Sosialisasikan Pembangunan Gedung di Sumbar
10Wakil Ketua DPR Terima Dubes Finlandia
-

DPR RI - DPR RI DESAK PEMERINTAH SEGERA BENTUK BADAN PANGAN NASIONAL
-

DPR RI - DPR RI HARUS ADA KONSEKUENSI HUKUM DARI HASIL SURVEY
-

DPR RI - BK DPR RI GELAR FGD DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SOLO
-

DPR RI - TIMWAS PMI DESAK PEMERINTAH BANGUN EARLY WARNING SISTEM BAGI PMI
-

DPR RI - WAKIL RAKYAT - SYAIFULLAH TAMLIHA
-

DPR RI - KOMISI IV DPR RI DUKUNG PERKEBUNAN CENGKEH DI MALUKU UTARA
VIDEO+
KPK Harus Cegah Upaya Korupsi
Selasa, 19 September 2017

KPK Harus Cegah Upaya Korupsi
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap banyak kepala daerah diharapkan menimbulkan efek jera. Namun sayangnya harapan itu sulit terwujud sebab aksi korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan kepala daerah masih banyak.
Ada sekitar 36 kepala daerah yang status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti. Karena situasi tersebut, pemerintahan hingga pembangunan di daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya lantaran tidak ada pemimpin di daerah.
“Konsekuensinya, program pembangunan di daerah tak jalan, sekaligus perekonomian semisal pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian akan mati. “Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto dalam dialektika demokrasi “Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?” bersama Komisioner Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagdja dan pengamat politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 September 2017.
Yandri mengakui untuk menang dalam pemilu begitu sulit jika tidak ada dana yang memadai. Sebab untuk kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) saja bisa membutuhkan Rp 285 miliar, yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaus, dangdutan, dan kebutuhan lainnya.
Karena itu banyak ditemukan jika kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat. “Kan tak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT KPK,” ujarnya.
Dengan situasi yang kerap terjadi itu, Yandri menyayangkan KPK tidak melakukan upaya pencegahan. KPK bersama Kepolisian sebaiknya membantu memprioritaskan upaya pencegahan aksi korupsi. Sehingga tidak semakin banyak kepala daerah yang menyalahgunakan anggarannya.
“KPK harus mengubah pola sehingga yang dilakukan adalah pencegahan dan mengurangi OTT. Buruk juga jika banyak kepala daerah terkena OTT,” ucapnya.
Rahmat juga mengakui biaya pilkada langsung itu sangat besar. Dampaknya pemilihan kepala desa (pilakdes) sampai RW pun saat ini dengan uang. “Bahkan jabatan RT atau RW dijadikan modal politik dalam setiap pilkada dan pemilu (pemilihan umum),” katanya.
Menurut dia tahun 2018 ini ada 171 daerah yang akan gelar pilkada dan biaya terbesar itu di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Belum lagi ditambah kalau terjadi pemungutan suara ulang (PSU) maka biayanya akan terus bertambah. “Untuk Papua Barat saja bisa Rp 15 miliar,” tuturnya.
Selama ini, partai politik sulit membuat laporan keuangannya sebab dana bersumber dari banyak tempat, antara lain perseorangan dan BUMD. Akibatnya Bawaslu kesulitan merumuskan pendanaan pilkada itu termasuk politik uang atau tidak.
Pangi juga setuju dengan usulan perbaikan KPK tersebut, tetapi dia menolak KPK dibubarkan. Mengingat Indonesia yang melakukan konsolidasi demokrasi. Saat ini kepercayaan rakyat pada DPR juga rendah dan berharap KPK dibenahi tanpa harus dibekukan. Untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, KPK memang perlu berfikir out of the box. Dia mengakui jika pesta demokrasi tingkat DPRD lebih berpeluang besar terjadi money politic. Jika money politic ini kemudian berdampak pada upaya pemenang pilkada mengembalikan “modal” maka akan semakin banyak kepala daerah terkena OTT. Dia menyontohkan kasus OTT yang terjadi di Bengkulu. Dengan singkatnya masa jabatan kepala daerah hanya satu hingga dua tahun saja, maka pemilih terbanyak di Bengkulu dipastikan adalah golongan putih (golput). Golput itu dipastikan bukan karena dari sisi teknis atau administrasi saja, akan tetapi juga secara ideologi. (*)
-

Monday, 12 March 2018
Peresmian Gedung Grha Suara Muhammadiyah
-

Wednesday, 23 November 2016
Wakil Ketua DPR RI Aher Gelar Coffee Morning Panas Bumi
-

Friday, 18 November 2016
Ketua DPR RI Ade Komarudin terima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
-

Tuesday, 08 November 2016
Diskusi Dialektika
-

Thursday, 20 October 2016
Kopi Darat DPR Bersama Kementerian dan Lembaga
-

Monday, 17 October 2016
Rapat Kerja Komisi VII DPR RI
FOTO TERKINI
PARLEMENTARIA+
MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA